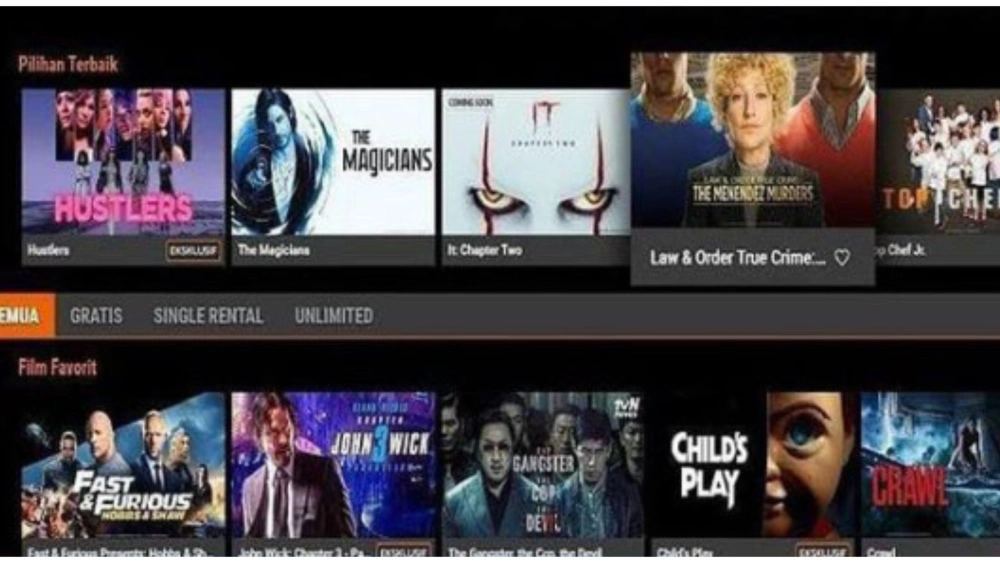Indonesia Sulit Capai Target Penurunan Emisi Karbon, Ini Penyebabnya

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Just Coalition for Our Planet (JustCOP) menagih komitmen pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi setara karbondioksida secara global yang memanaskan bumi.
Dengan kebijakan energi saat ini, puncak tertinggi emisi karbon Indonesia yang seharusnya dicapai pada tahun 2030, justru diprediksi mundur hingga tahun 2037.
Semestinya setiap negara memetakan puncak tertinggi emisi karbon sebelum turun melandai demi mencegah pemanasan bumi yang berakibat fatal bagi peradaban manusia. Namun komitmen Indonesia saat ini justru sebaliknya.
Baca Juga: Banjir Tak Kunjung Usai, Kerusakan Lingkungan Sumatera Disorot
“Puncak tertinggi emisi sektor energi Indonesia ditargetkan mundur tujuh tahun dari proyeksi dalam strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim sampai 2050 (Long Term Strategy -Low Carbon and Climate Resilience - LTS -LCCR),” ujar Syaharani, Kepala Divisi Iklim dan Dekarbonisasi, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dalam diskusi daring di Jakarta (14/10/25), dilansir Tim Komunikasi JustCOP.
Turut hadir dalam diskusi tersebut Tri Purnajaya, Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri dan Torry Kuswardono, Koordinator Sekretariat Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim.
Rencana Ketenagalistrikan Indonesia RUKN 2024-2060
Kemunduran target yang Syaharani sampaikan merujuk pada Rencana Ketenagalistrikan Indonesia terbaru (RUKN 2024-2060) yang menyebutkan bahwa produksi listrik dari PLTU diperkirakan melonjak dan mencapai puncaknya pada 2037.
Ia juga merujuk Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menyebutkan bahwa 79% bauran energi pada 2030 masih berasal dari energi fosil.
“Saat ini, target penurunan emisi karbon Indonesia dengan proyeksi Business as Usual (BAU) pada 2030 masih merefleksikan kenaikan emisi 148% bila dibandingkan dengan emisi karbon pada 2010,” kata Syaharani.
Selain itu, dokumen ENDC yang berlaku saat ini belum secara spesifik menyebut target pensiun dini pembangkit listrik batubara, yang mendominasi penyedia listrik di berbagai sektor industri di Indonesia.
Dengan mundurnya target ini, Syaharani melanjutkan, sektor energi yang menjadi penyumbang emisi terbesar masih akan membuang emisi lebih besar lagi. Ini sudah pasti melampaui tolak ukur batas kenaikan suhu sebesar 1.5 derajat celcius dari masa pra industri.
“Artinya, jika target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Indonesia yang dibuat pada 2022 terpenuhi, Indonesia sebenarnya masih menghasilkan emisi cukup signifikan,” kata Syaharani.
Bumi Memanas dan Krisis Iklim Semakin Parah
Kenaikan emisi mengakibatkan bumi memanas dan krisis iklim akan semakin parah. Karena itu, JustCOP mendorong agar pemerintah segera meningkatkan target komitmen penurunan emisi Indonesia melalui Second Nationally Determined Contribution (SNDC).
Indonesia Lampaui Tenggat Penyerahan Dokumen SNDC
Menjelang konferensi para pihak untuk perubahan iklim (COP 30) yang akan berlangsung pertengahan November 2025 kelak, sampai pertengahan Oktober saat ini Indonesia belum juga menyerahkan dokumen SNDC. Tenggat penyerahan telah terlewati, yakni bulan September 2025 yang lalu.
Namun, Tri Purnajaya, Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri optimis Indonesia akan segera menyerahkan dokumen tersebut.
Ia mengingatkan agar publik harus realistis karena Indonesia masih terus menggenjot pertumbuhan ekonomi.
“Komitmen Indonesia harus diselaraskan dengan target pembangunan 8%. Kita bukan satu-satunya yang belum menyerahkan dokumen SNDC, baru setengah (dari negara-negara yang menyepakati Perjanjian Paris) yang menyerahkan,” katanya.
Kebijakan harus Berpihak pada Masyarakat
Dalam diskusi itu, Torry Kuswardono menekankan kebijakan iklim wajib berpihak pada masyarakat. Mitigasi yang dilakukan pemerintah tidak seharusnya menyebabkan pelemahan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.
Pemerintah semestinya melindungi hak atas tanah melalui pengakuan tanah adat dan reforma agraria sebagai fondasi ketahanan iklim komunitas.
Juga perlindungan sosial adaptif bagi subjek rentan seperti warga disabilitas, buruh, dan pekerja informal. “Sepuluh tahun terakhir pada tingkatan akar rumput terjadi pelemahan dalam adaptasi masyarakat menghadapi perubahan iklim,” kata Torry yang juga Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL.
Ia mencontohkan hilirisasi nikel di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah justru menjadi perebutan tanah, memicu konflik agraria, dan berdampak pencemaran pada masyarakat sekitar. “Perlindungan terhadap kelompok rentan tidak terlihat dalam kebijakan perubahan iklim di Indonesia,” katanya.
Torry juga menyoroti persoalan kurangnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan Indonesia. “Ada mekanisme-mekanisme yang tidak cukup transparan. Kalau pun ada partisipasi, itu tokenisme, alias partisipasi semu. Prosesnya kita tidak tahu. Hari ini diumumkan akan ada partisipasi publik, besoknya sudah ketok palu kebijakan disahkan,” katanya.
Torry juga mengimbau pemerintah lebih fokus pada kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk proyek-proyek yang lebih kecil tetapi masif dan inklusif, bukan proyek-proyek besar terpusat.
“Komunitas lokal lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bukan pelepasan lahan untuk proyek ketahanan pangan dengan membabat hutan, yang seharusnya dijaga karena kekayaan biodiversitasnya,” kata Torry.