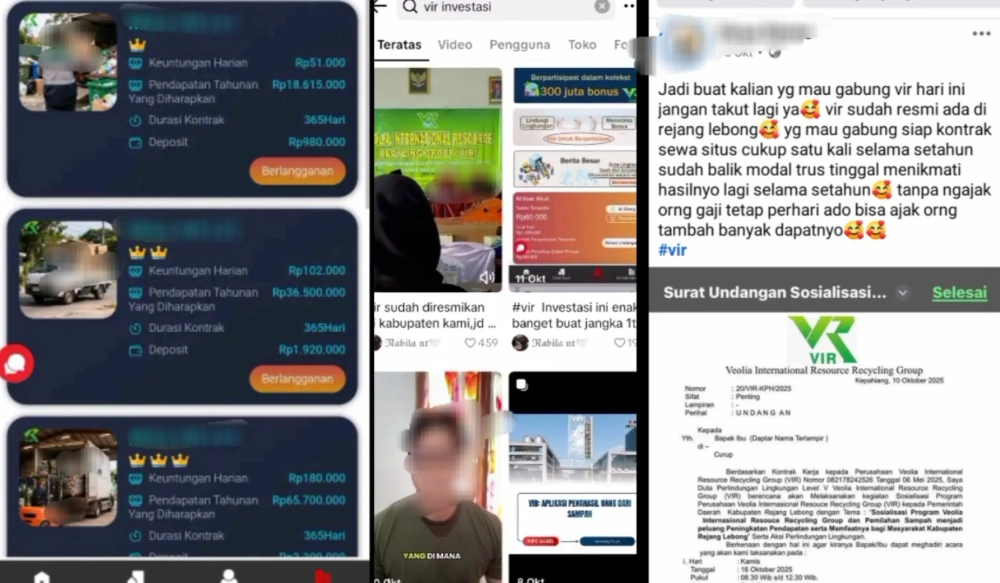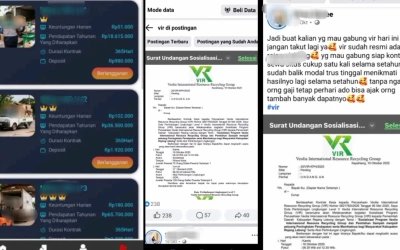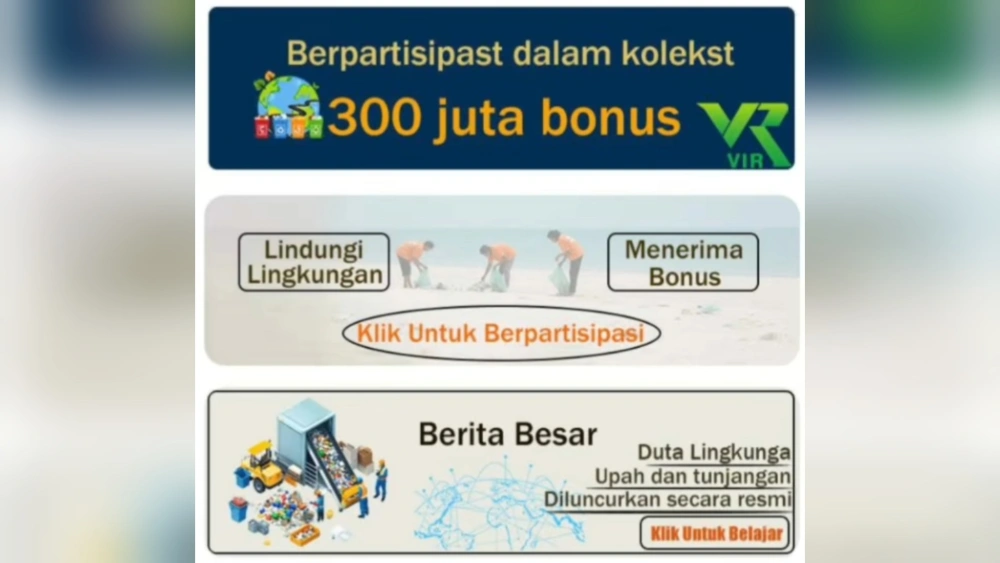Yokbeth Felle Nilai Negara tak Serius Lindungi Hak Masyarakat Adat

Masyarakat Adat meragukan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengakuan hutan adat seperti yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 4 November 2025 dalam pembukaan ajang konferensi iklim COP 30 di Brazil.
Sebab, kebijakan negara dalam mengelola tanah dan hutan adat belum berpihak pada perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dan adil berkelanjutan.
Dalam Diskusi Mingguan Nexus Tiga Krisis Planet: #TheAnswerisUs: Suara Masyarakat Adat Bagi Keadilan Iklim yang diadakan Rabu, 12 November 2025, Yokbeth Felle, Staf Kampanye Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, mengatakan bahwa negara tidak serius dalam memenuhi, memajukan, menghormati, dan melindungi hak Masyarakat Adat.
Menurut Yokbeth, konsep penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat Adat seharusnya dimulai dari melihat kembali hubungan relasi antara masyarakat adat, hutan, dan tanah.
Selama ini umumnya hubungan tersebut hanya dilihat manusia sebagai subjek, sedangkan hutan dan tanah adalah objek. Padahal, Masyarakat Adat mempunyai pandangan berbeda terhadap hutan dan tanah. Mereka memandang hutan dan tanah sebagai ibu bahkan ada yang menganggapnya sebagai bagian dari tubuh.
“Ini merupakan ungkapan yang disampaikan oleh salah satu pemuda suku Moi di wilayah Sorong. Ia menegaskan bahwa kalau sampai tanah hilang, berarti marga yang meninggali tanah itu juga hilang,” kata Yokbeth, dikutip dari siaran pers JustCOP (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim).
Hubungan Perempuan Adat Suku Yei dengan Alam
Yokbeth juga mencontohkan hubungan Perempuan adat di Suku Yei di Merauke, Papua Selatan, dengan alam. Salah satunya dengan pohon nibung atau yang disebut dengan tarek dalam bahasa suku Yei. “Nibung ini dapat di hutan, makanya mama tidak suka dong (mereka) bongkar hutan,” kata Yokbeth menirukan ucapan Mama Alowisia, perempuan adat Suku Yei.
Nibung menjadi penting bagi Mama Alowisia karena nibung ini digunakan untuk menampung air pati sagu. Mama Alowisia tidak mau hutannya dibongkar karena ia akan kehilangan alat produksinya yang membantunya mempersiapkan bahan pangan bagi keluarga.
Pohon nibung berfungsi untuk menahan abrasi dan erosi, sebagai penyaring air alami, habitat bagi burung, serangga, biota air, serta sebagai penyerap karbon.
 Perempuan masyarakat adat Namblong di wilayah adat Grime Nawa, Lembah Grime, Papua, memanen sagu.(Foto: Dokumentasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)Menurut Yokbeth, relasi Masyarakat Adat dengan hutan adat dan tanah juga bersifat emosional dan spiritual. Relasi ini menunjukkan ketergantungan Masyarakat Adat pada hutan dan tanah. Ketika ada proyek ekstraktif di atas tanah mereka, Masyarakat Adat menjadi terasing dari alat produksinya sendiri karena dalam logika kapitalisme, hubungan Masyarakat Adat, hutan, dan tanahnya adalah subjek dan objek.
Perempuan masyarakat adat Namblong di wilayah adat Grime Nawa, Lembah Grime, Papua, memanen sagu.(Foto: Dokumentasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)Menurut Yokbeth, relasi Masyarakat Adat dengan hutan adat dan tanah juga bersifat emosional dan spiritual. Relasi ini menunjukkan ketergantungan Masyarakat Adat pada hutan dan tanah. Ketika ada proyek ekstraktif di atas tanah mereka, Masyarakat Adat menjadi terasing dari alat produksinya sendiri karena dalam logika kapitalisme, hubungan Masyarakat Adat, hutan, dan tanahnya adalah subjek dan objek.
“Selain itu, selama ini aturan-aturan yang diterbitkan oleh negara juga menciptakan regulasi yang melayani pasar, di atas negara ada modal, dan negara merasa menguasai Masyarakat Adat sebagai warga negara dan hutan adat sebagai hutan negara,” katanya.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat telah mendampingi dan mengurus penetapan hutan adat Komunitas Gelek Malak Kalawis Pasa di Sorong, Papua Barat Daya, sejak beberapa tahun yang lalu dan sub suku Afsya di Sorong Selatan.
Usulan Penetapan Hutan Adat ke Kemenhut belum Direspon
Pusaka dan Masyarakat Adat sudah mengajukan usulan penetapan hutan adat kepada Kementerian Kehutanan di Jakarta. Proses ini membutuhkan waktu yang lama, biaya yang mahal, terutama karena jaraknya sangat jauh.
Dalam catatan Pusaka selama satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran belum ada penetapan hutan adat di Papua. Capaian penetapan hutan adat di seluruh pulau Papua mulai 2016 hingga Oktober 2025 hanya mencapai angka 39.912 ha.
Angka tersebut belum termasuk usulan hutan adat yang Pusaka dampingi yakni di Sorong dan Sorong Selatan. Ini ironis, setelah 13 tahun putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan hutan adat di Papua baru hanya seluas 39,9 ribu hektare dari potensi luasan 12,466 juta hektar.
Bandingkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk mendukung Proyek Ekstraktif di Provinsi Papua Selatan seluas 587.750 hektar yang kontradiktif dan berlangsung di wilayah adat.
“Jadi proses untuk memberikan izin pada proyek ekstraktif itu lebih cepat dibandingkan dengan memberikan pengakuan hutan adat. Bahkan Papua Selatan sebagai provinsi baru dipaksa untuk merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah untuk mempercepat kawasan budi daya seluas sepuluh juta hektare lebih untuk mengakomodasi perluasan proyek ekstraktif,” tuturnya.
Jangan Anggap Masyarakat Adat Terbelakang
Erasmus Cahyadi, Deputi II Bidang Advokasi dan Politik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menambahkan, pengakuan hutan adat sendiri hanya sebagian dari permasalahan Masyarakat Adat yang kompleks.
Hutan adat adalah salah satu bagian dari wilayah adat yang dimiliki oleh Masyarakat Adat. Mereka seringkali menghadapi intimidasi dan kriminalisasi ketika ada perusahaan masuk ke dalam wilayah adat tersebut.
Padahal, kata Erasmus, Masyarakat Adat merupakan jawaban atas krisis iklim saat ini. Menurutnya, sejak lama Masyarakat Adat telah menjaga hutan dengan kearifan lokal mereka.
“Yang dibutuhkan adalah jangan mengganggu praktik baik yang dilakukan oleh Masyarakat Adat. Jangan menganggap bahwa Masyarakat Adat itu terbelakang,” ujarnya.
Working Group (ICCAs- Indigenous Peoples and Local Communities Conserved Territories and Areas) Indonesia (WGII) juga mengidentifikasi model-model kearifan lokal dalam perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati seperti yang dijelaskan oleh Erasmus Cahyadi.
Kontribusi Masyarakat Adat dalam Mengatasi Problem Iklim Masih Minim
Per Mei 2025, terdapat Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM) dengan luasan 647.457,49 hektar yang terdokumentasi dan terdaftar di WGII, dari total potensi mencapai 22,8 juta hektar. Praktik konservasi yang dilakukan oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal ini merupakan solusi dari level akar rumput, yang seharusnya diakui dan dipromosikan oleh negara,” tambah Mega Ayu Lestari, Staff kampanye WGII.
Namun, sayangnya kontribusi Masyarakat Adat dalam mengatasi problem iklim minim pengakuan, salah satunya akibat ketiadaan undang-undang yang secara khusus mengatur urusan pengakuan Masyarakat Adat.
Menurut Erasmus, saat ini pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi mendesak dan harus diprioritaskan dan Kementerian Kehutanan bisa mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat yang telah lama tertunda.
Respon Dirjen Perhutan Sosial: Keterbatasan SDM
Julmansyah, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan mengatakan, salah satu masalah yang memperlambat proses pengakuan hutan adat adalah keterbatasan sumber daya yang ada di masyarakat dan pemerintah daerah.
Menurut dia, problem ini bisa disiasati dengan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil yang memiliki sumber daya tersebut. Kementerian Kehutanan juga memberikan pelatihan untuk menambah verifikator untuk mempercepat proses verifikasi usulan pengakuan hutan adat.
Saat ini Kementerian Kehutanan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penetapan Status Hutan Adat yang terdiri dari kementerian, akademisi, praktisi, serta mitra, termasuk organisasi masyarakat sipil.
Kementerian menargetkan percepatan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029 sebagai bagian integral strategi nasional memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat. “Basis dari pengakuan tersebut adalah permohonan usulan, ada luasnya, petanya,” katanya.
Julmansyah mengatakan, target 1,4 juta hektare merupakan hasil diskusi dari organisasi masyarakat sipil yang sudah memiliki data tentang daerah yang sudah memiliki peraturan tentang pengakuan dan penetapan hak masyarakat adat, surat keputusan pengakuan tersebut, peta wilayah adat dan lainnya.
Saat ini Kementerian telah menyusun roadmap percepatan penetapan status hutan adat. “Desember 2025 nanti rencana kami melakukan konsultasi publik untuk draft roadmap-nya,” katanya.